Buku Ngebir Sebelum Sholat: 30 Kisah Rasa untuk Hari Kemerdekaan ke-80 RI
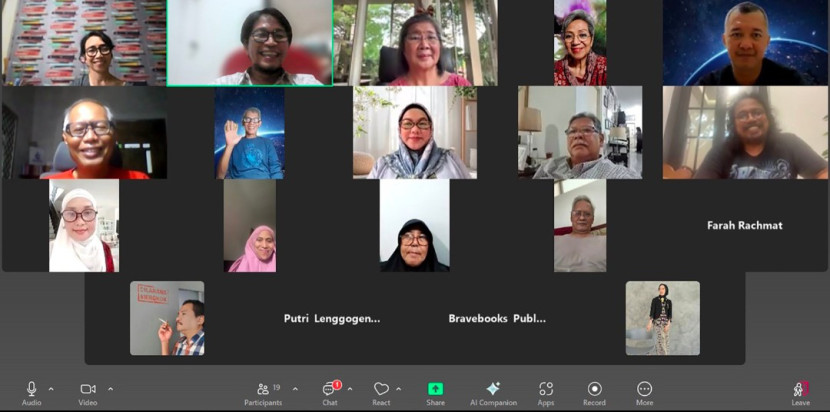
RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Di layar Zoom itu, wajah-wajah muncul berjejer dalam kotak-kotak kecil, ada yang mengenakan kaus oblong, ada yang bersolek cantik, ada yang berbusana batik, ada pula yang sengaja menyalakan latar bendera merah putih.
Di satu kotak, terdengar suara sendok beradu dengan gelas; di kotak lain, seorang teman melambaikan tangan ke kamera.
Seperti hajatan kampung yang pindah ke ruang maya, suasananya terasa hangat, riuh, sekaligus intim.
Ada yang menyalakan mikrofon tanpa sengaja, membuat suara ayam berkokok di belakang terdengar jelas, disambut tawa peserta lain.
Baca juga: Indonesia Raih Perunggu di Kejuaraan Speed Slalom International di Lishui China
Ada pula yang baru saja pulang belanja, kantong plastiknya masih berserakan di meja, tapi tetap sempat masuk ke ruang virtual demi ikut merayakan lahirnya buku ini.
Dari satu layar terdengar obrolan beberapa orang, dari layar lain tampak seorang penulis tersenyum lebar sambil mengangkat gelas berisi minuman jahe panas, seolah ingin bersulang dengan semua orang.
Begitulah suasana pada Ahad sore, 17 Agustus 2025, ketika sebuah peluncuran buku berlangsung bukan di aula hotel, bukan di gedung kesenian, apalagi di resto atau kafe melainkan di ruang maya bernama Zoom.
Dari kotak-kotak layar yang saling menyapa, terdengar seruan akrab Om Bud!, sapaan untuk Budiman Hakim, penulis produktif lebih dari 20 judul buku, penggagas komunitas penulis The Writers sekaligus moderator acara bertajuk “Peluncuran Seri ke-2 Antologi Kisah Rempah Kita Nusantara: Ngebir Sebelum Sholat, persembahan Rempah Kita, The Writers dan penerbit BraveBook”.
Baca juga: Hari Kemerdekaan, 862 Warga Binaan Rutan Depok Terima Remisi, 36 Langsung Bebas
“Merdeka, merdeka, merdeka ! Hari ini Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-80 Republik Indonesia (RI) . Dan para penulis dalam lingkar The Writers merayakannya dengan cara berbeda: melahirkan sebuah antologi berjudul “Ngebir Sebelum Sholat”, begitu kalimat awal Om Bud dalam ruang Zoom menandai secara resmi buku ini diluncurkan pada Ahad (17/08/2025).
Judul Mengguncang, Isi yang Menenangkan
Judulnya mencengangkan, seakan hendak menantang keyakinan. Ngebir sebelum sholat?
Siapa yang berani? Namun ketika halaman dibuka, kita mendapati sesuatu yang justru menenangkan.
Buku ini tidak sedang mengajak orang untuk menenggak bir hingga mabuk, melainkan mengajak kita pulang, lewat jalan paling sederhana, minuman atau makanan khas bumi pertiwi.
Adalah Asep Herna yang menulis kisah dengan judul sama seperti sampul buku. Ia membuka dengan kalimat yang terdengar seperti pengakuan dosa.
“Siapakah yang pernah mempersatukan Ustaz dan Sang Pemabuk dalam satu ritual minum Bir? Saya pernah!”
Namun ternyata bir yang dimaksud Asep adalah Bir Kotjok, minuman khas Bogor berbahan jahe, kayu manis, gula aren, dan soda. Cairannya keemasan, bergelembung, berbuih mirip bir Eropa, tapi halal dan hangat.
Baca juga: Catatan Cak AT: Merayakan Endek Bali
Di trotoar jalan Surya Kencana sebagai sentra kuliner kota hujan Bogor, Asep duduk bersama dua sahabat lama yang dulu nyaris saling hantam karena minuman haram. Hari itu mereka bersulang lagi, menukar dendam dengan tawa.
“Ngebir Sebelum Sholat” bukan buku resep. Ia adalah 30 kisah hidup yang dituturkan lewat kuliner khas Nusantara, disajikan 22 penulis dari berbagai kota.
Ristanto Dedy menulis tentang “Rendang dan Takdir yang Mengunyah”. Rendang legam di etalase rumah makan Padang Semarang bukan sekadar lauk, melainkan janji yang lama tertunda, sampai satu suapan mengubah arah hidup.
Devina Hakim bertutur dalam tulisannya “Rendang Extravaganja”. Rendang ini bikin ketagihan, entah karena bumbunya atau ‘daun rahasia’ di dalamnya.
Baca juga: Naturalisasi Anak Depok Sebentar Lagi Final, Siap Bertarung di Round 4 Piala Dunia
Dari warisan nenek, perjalanan lintas benua, hingga ide iseng memetik dua pot kecil di tepi jendela, lahirlah rendang yang membuat meja makan penuh tawa. Malam itu semua pulang dengan perut kenyang dan rahasia yang tak semua berani mengakuinya.
Lily Setiadinata menghadirkan “Gudeg, Tangan dan Waktu”. Di Jogja, katanya, manis lahir dari kesabaran. Gudeg dimasak tanpa terburu-buru, seolah waktu ikut mengaduk di kuali.
Setiap suapan menyimpan rindu yang diam-diam pulang, bersama rahasia rasa yang tak akan ditemukan di tempat lain.
Fraya menulis “Cinta dalam Semangkuk Ceker Setan”. Pedasnya membakar, tapi di situlah ia menemukan keberanian menelan sakit. Ternyata, ceker bisa lebih pedas dari pengkhianatan.
Baca juga: 80 Tahun Kemerdekaan, Lapangan Pekerjaan untuk Semua Topang Pilar Indonesia Emas 2045
Di balik mangkuk kecil berisi kaki ayam, tersimpan keberanian untuk menelan rasa sakit demi menemukan nikmat yang tak terlupakan.
Pedas yang membakar, rempah yang memeluk, dan kenangan yang menyelinap di tiap gigitan ceker setan ini bukan sekadar hidangan, tapi jeda yang membuat hati kembali bernapas. Dan Djoni Satria membawa kita ke Sumatra lewat “Tempoyak: Jalan Rindu untuk Pulang”.
Fermentasi durian yang tajam ini bukan sekadar lauk, tapi surat cinta dari masa kecil. Asamnya mengoyak, aromanya membelah dunia tapi di situlah rumah.
Fermentasi durian yang tajam ini memanggil rimba dan sungai-sungai Sumatra, dapur ibu-ibu, dan kenangan masa kecil. Tak semua bisa mencintainya, tapi bagi yang tumbuh bersamanya, tempoyak adalah surat cinta yang dibaca lewat lidah.
Baca juga: Teater Sastra UI Alumni UI Lintas Generasi akan Persembahkan Malam Dzikir Puisi
Ada pula Nylla Suis dengan “Perang Empek-empek Kapal Selam”, di mana rebutan telur bisa lebih sengit daripada lomba 17 Agustus.
Ada Luqman Baehaqi dengan “Pesan Perdamaian dari Mangkuk Hitam”, yang melihat rawon kelam sebagai simbol damai: dibaca terbalik, namanya justru mengajak - NO WAR.
Masih ada beberapa penulis lagi fiantaranya: Angelica Lovelynda, Ati Kisjanto, Aris Heru Utomo, Binny Buchori, Clara Cussoy, Dini Novita, Kepra, Melati ER, Nadia, Nina Masjhur, Pritha Kalidha, Vifi Cemal dan Winda Zuchra. Mereka piawai memasak kata, sajiannya layak untuk dibaca.
Melahap habis semua hidangan dalam buku ini tentu akan mengenyangkan jiwa.
Baca juga: Meriahkan Hari Kemerdekaan ke 80 RI Digelar Pameran Lukisan di Tamini Square
Karakter di Balik Kisah
Buku ini kaya bukan hanya karena kisah, tapi juga karena warna-warni penulisnya.
Budiman Hakim dengan “Mabuk Kepayang”, menulis dengan humor khasnya tentang semangkuk kuah hitam yang membuat orang jatuh cinta. Siapa sangka racun bisa membuat orang jatuh cinta dan ketagihan?
Semangkuk kuah hitam pekat duduk di meja, awalnya tampak seperti sesuatu yang sebaiknya dihindari. Tapi sekali suap, ada yang berubah.
Antara tawa sahabat yang sedang dimabuk cinta dan rahasia biji kepayang, hari itu saya pulang dengan kepala ringan dan hati yang tak ingin cepat sadar.
Baca juga: Muhasabah Kemerdekaan: Homo Socius dan Homo Homini dalam Kemerdekaan
Lily Setiadinata, pemerhati kuliner, yang selalu bisa mengubah nasi uduk sederhana menjadi cerita pulang.
Asep Herna, yang berani membuka buku dengan judul “provokatif” namun bermakna damai. Nadia Iskandar, yang begitu ‘sexy’ judulnya, “Hadiah langsing tanpa diundi”.
Djoni Satria, yang menghadirkan asam tempoyak sebagai jalan pulang bagi mereka yang rindu pada Ibu.
Kuliner sebagai Cermin Bangsa
Di balik setiap kisah, tersimpan refleksi kultural. Bir Kotjok dan Bir Pletok adalah contoh bagaimana bangsa ini berani melawan kolonialisme gaya hidup Eropa.
Baca juga: Prabowo Ajak Partai Koalisi Awasi dan Kritik Pemerintah Demi Jaga Demokrasi
Orang Betawi dan Bogor meracik minuman mirip bir, tapi halal. Mereka tidak sekadar meniru, melainkan mencipta sesuatu yang lebih sesuai jiwa mereka.
Demikian pula kuliner Nusantara lainnya. Nasi kuning, sayur asem, sambal takokak, yang dulu sering dianggap “kampungan”, padahal menyimpan daya hidup luar biasa. Saat krisis pangan, umbi-umbian sederhana itulah yang menyelamatkan banyak keluarga.
Seperti kata Lily dalam sambutannya, “Tiga puluh kisah ini bukan sekadar tentang makanan.
Ia tentang rumah yang kadang bukan alamat, tentang rindu yang diam-diam dibungkus daun pisang, dan tentang rahasia yang disampaikan tanpa kata hanya lewat suapan”.
Baca juga: Catatan Cak AT: Panggung Dunia eSport di Riyadh
Kado Kemerdekaan
Peluncuran buku ini sengaja dilakukan di Hari Kemerdekaan. “Kami ingin memberi
kado kecil untuk Indonesia 80 tahun merdeka,” kata Om Bud yang tak bosan mengkampanyekan tagline The Writers, “Sebelum Mati Buatlah Minimal Satu Buku”.
Makanan adalah cara paling sederhana merayakan bangsa. Di meja makan, semua duduk sama rendah. Di meja makan, tak ada perbedaan. Makanan membuat kita bangga sebangsa dari rendang Padang, rawon Jawa, hingga tempoyak Sumatra.
Membaca “Ngebir Sebelum Sholat” seperti menghadiri pesta panjang. Ada tawa, ada air mata, ada pedas yang bikin berkeringat, ada manis yang membuat hati pulang. Dan setelah menutup bukunya, kita tak hanya ingin mencoba resep.
Baca juga: PQN 2025 Bank Indonesia Cirebon Usung Semangat Majalengka Langkung Sae, Dorong Digitalisasi UMKM
Kita ingin menelpon Ibu, ingin masuk ke dapur nenek, ingin menyantap makanan sederhana yang tiba-tiba jadi sangat mahal nilainya.
Karena makanan dalam buku ini adalah cara paling jujur untuk merayakan hidup. Setiap kuliner dalam buku ini seperti sehelai kain kecil.
Tempoyak kuning yang asam, rawon hitam pekat, gudeg cokelat manis, nasi kuning yang cerah semuanya berkibar bersama, menjahit Indonesia dalam rasa.
Merdeka 80 tahun bukan hanya soal mengibarkan bendera di tiang bambu, tapi juga menjaga bendera rasa ini tetap berkibar di meja-meja makan kita. Karena di sanalah kita belajar tentang persatuan; satu piring dibagi ramai-ramai, satu gelas bir kotjok diangkat bersama, satu lauk sederhana cukup membuat semua tertawa bahkan rasa bahagia yang dapat membalut jiwa.
Baca juga: 80 Tahun Merdeka, Saatnya Ketahanan Pangan "Naik Kelas" Jadi Kemandirian Pangan
Kalau di lapangan upacara kita hormat pada merah putih, maka di meja makan kita hormat pada sajian ibu. Perayaan kemerdekaan boleh dihiasi aneka lomba, ragam pesta, menyalakan kembang api guna menambah kemeriahan.
Tapi setelah semuanya selesai, yang menyatukan kita kembali adalah bisa saja semangkuk sayur asem, sepiring nasi uduk atau segelas bir pletok.
Itulah pesta kemerdekaan yang paling sederhana, tapi sekaligus paling jujur, pesta di meja makan Nusantara. (***)
Penulis: Djoni Satria






 Bisnis - 45 menit lalu
Bisnis - 45 menit lalu


